Demi menghindari rusaknya kehidupan, rasanya sementara waktu, pendekatan koersif masih kita butuhkan.
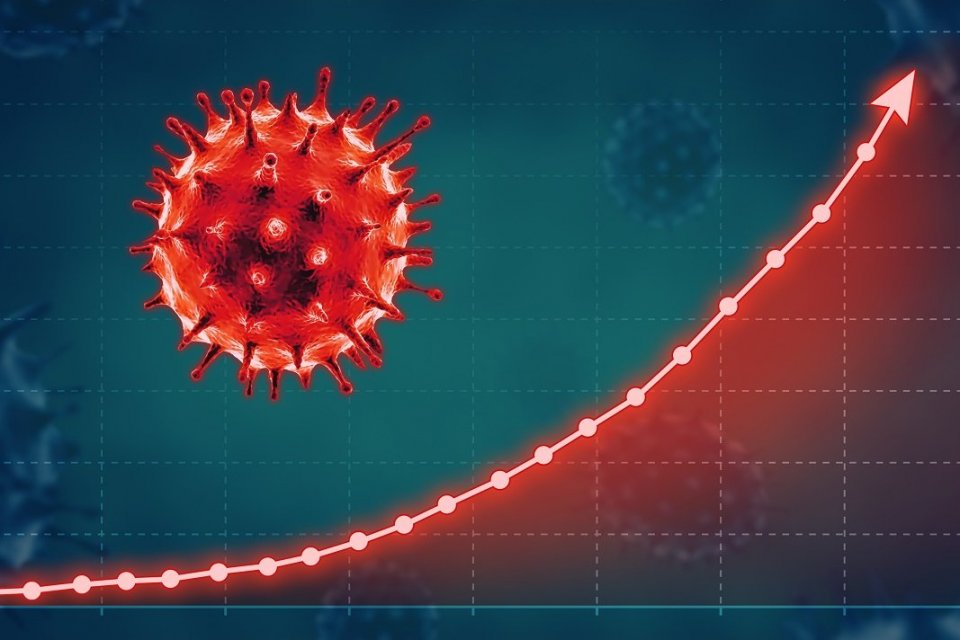
Di tengah kian tak terbendungnya wabah Covid-19, sejumlah langkah, program dan agenda dipetakan. Terus terang, kita tergagap, tak pernah menyangka, eskalasi sebarannya akan sehebat dan sekuat ini. Rasa kaget dan ketergagapan lahir akibat abai dan bebalnya semua pihak, pemerintah dan rakyat, saat pertama mengidentifikasi virus yang berkembang dari Wuhan, China ini.
Pernahkah Anda membayangkan seorang anggota kabinet menyebut virus corona tak akan menyeberang ke Tanah Air ? Dengan alasan akan segera tewas begitu sampai di bibir pantai tropis ? Demikian lemahnya virus itu dalam pandangannya, sehingga cukup dihadang dengan doa dan jampi, maka pasukan makhluk “halus” itu akan langsung tewas sebelum sempat menginjak daratan.
Kalau saja pemerintah memiliki kepekaan dan visi yang baik tentang pola penyebaran dan pola penanggulangannya sejak pertama China terguncang, tentu kita tak akan senaif sekarang. Andai kata masyarakat sejak awal sudah terbiasa dengan pola hidup, pola pikir dan pola makan sehat, tentu tak akan sehoror saat ini, meski pemerintahnya panik.
Ironisnya, karena kepanikan terus tumbuh membesar, menyebut pihak tertentu sebagai biang kesalahan, dianggap tabu dan tidak produktif. Kita sering lupa, pada zamannya, orang merdeka supaya dapat memahami situasi, cukup diberi isyarat. Tapi bagi para hamba sahaya, mesti disiapkan alat untuk menghardiknya. Dalam situasi ketergagapan, bukankah semua kita adalah hamba sahaya?
Haruskah rakyat menjerit, agar pemerintah lekas pintar mengelola kepentingan bersama? Mestikah pemerintah menggunakan tongkat untuk menghardik rakyat agar cepat beranjak dari kelalaiannya? Kalau saja pemerintah bertekad dan menyadari amanahnya sambil membatin, “Tuhan! Hamba mendengar firman-Mu, dan hamba taat.”
Kalau saja masyarakat memaknai ketaatan kepada pemerintah sebagai salah satu pesan sosial dari semua gerakan ritmis dalam ritual, tentu situasinya tak akan sekritis saat ini. Alangkah nestapa jika ajaran agama suka ditafsir sesuai maunya awak dan kepentingan. Amboi, andai sebagai rakyat, kita bisa berseru, “Daulat, Tuhanku! Kami mendegar semua seruan-Mu. Kami taat patuh.”
Sekarang, semua berbicara dan tak tak ada yang mau mendengarkan. Hanya mau didengarkan. Dalam rumah tangga, ketegangan kerap muncul karena semua pihak hanya mau bicara dan tidak mau mendengarkan. Dalam organisasi, bencana sering terjadi karena para eksekutif baru merasa eksis kalau tiada henti berbicara dan menolak mendengarkan suara orang selain suara dirinya. Ingin citra dirinya terjaga baik.
Sedih hati ini menyaksikan setiap hari kalangan profesional sektor kesehatan dan rakyat terus didera rasa takut bahkan bertumbangan karena merebaknya virus Covid-19 ini.
Idiom dalam frase “Saya Mendengar dan Saya Patuh”, bisa dijadikan pelecut untuk merenungi apa yang mungkin kita lakukan ketika banyak saudara sebangsa bertumbangan. Paling tidak, memikirkan di mana posisi kita dalam ikhtiar memutus rantai penyebaran virus corona. Agar efektifitas agenda berjalan baik, maka dibutuhkan daya kejut yang mampu menampar kesadaran bersama bahwa tak ada jaminan seseorang terbebas dari ancaman virus corona ini.
Simak dengan seksama, contoh terbaik dalam mengalahkan Covid-19 yang dilakukan dua negara, meski berbeda ideologi, China dan Korsel. Menggunakan pola komando sentral, China menerapkan konsep “menutup diri” dengan mekanisme lockdown. Pola ini berjalan efektif, karena faktor kepemimpinan satu komando. Meski berbau otoriter, program tersebut terbukti memang ampuh.
Tetangganya, Korea Selatan juga menuai sukses meski dengan pendekatan berbeda. Minus komando sentral seperti China karena Korea Selatan menganut sistem demokrasi, negara ginseng mengambil manfaat dari mekanisme self isolation dan social distancing.
Karena sistem demokrasi prosedural dan substansial berjalan normal, rakyat teredukasi dengan baik. Virus dicegah sebelum memangsa korban lebih banyak.
Bagaimana dengan Indonesia ? Penulis teringat satire tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi (alm) kala menyebut Indonesia sebagai negara bukan-bukan. Negara otoritarian bukan, negara demokrasi bukan, negara kerajaan bukan. Tapi praktek otoritarianisme, demokrasi dan feodalisme, bisa hidup dalam satu kamar di negeri ini. Begitu ditimpa bencana seperti saat ini, kita semua menanggung akibatnya.
Mengacu pada Korea Selatan yang negara demokrasi, kita harusnya tak memerlukan konsep lockdown untuk membuat virus corona takluk. Tapi apa yang terjadi ? Wabah yang sudah pandemik, malah menjelma bursa perang gagasan. Di Korea Selatan, karena warganya sudah teredukasi, program penanggulangan pemerintah bertemu di muara harapan rakyat. Tanpa suara. Diam dan bekerja.
Oleh sebab itu, karena status darurat, demikian teman-teman di NU berdalil, maka menghindari kerusakan harus lebih dipentingkan dibanding harapan tercapainya kemaslahatan. Demi menghindari rusaknya kehidupan, rasanya sementara waktu, pendekatan koersif masih kita butuhkan. Mungkin kita masih butuh digedor untuk berucap, “Saya Mendengar, Saya Patuh.”
Disclaimer: Opini ini telah ditayangkan sebelumnya di tempo.co edisi 1 April 2020
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews