Menulis karya fiksi membutuhkan penghayatan perasaan dan penggunaan pelbagai penalaran. Ada hal-hal krusial di luar penulisan berita pada umumnya seperti: penyelarasan imajinasi dan fakta.
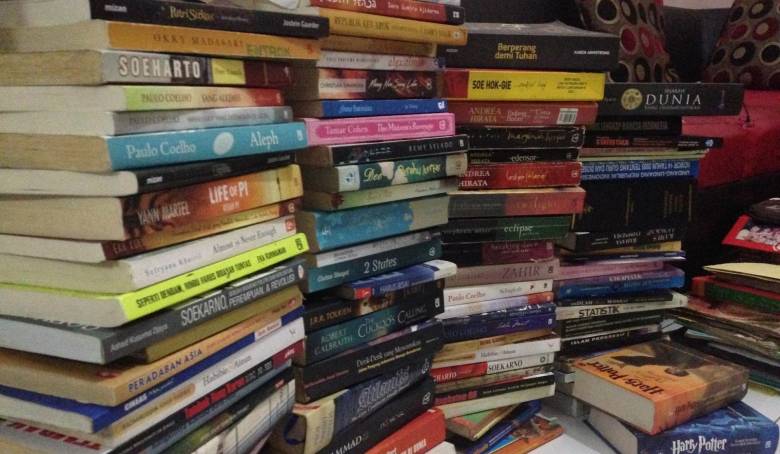
Membaca sebuah novel, sama seperti ketika kita menyelesaikan sebuah perjalanan panjang dan melelahkan. Ketimbang melumat puisi dan cerita pendek, menamatkan novel biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Dengan kata lain, pembaca novel adalah pembaca simpatik. Mereka mau mendengarkan sebuah cerita panjang, sembari berkompromi dengan waktu dan keadaan.
Tapi sebagai pembaca novel, saya punya sikap pribadi. Saya punya psikologi membaca sendiri. Untuk membaca suatu novel misalnya, saya mesti mengondisikan waktu dan situasi sekitar. Terkadang saya harus menyingkir dari kerumunan sementara waktu demi menciptakan ketenangan. Dari ketenangan itu, saya bisa menamatkan novel yang saya miliki satu per satu.
Ketika bertemu dengan novel menarik dan ditulis oleh cara-cara yang menyenangkan, saya akan larut dalam cerita dan bisa mengulanginya secara singkat. Tetapi ketika saya bersua dengan novel yang membuat suntuk, saya akan meletakkannya sementara waktu, dan melanjutkannya di kemudian hari. Sebab, selalu ada optimisme dan harapan baik untuk semua novel yang sudah mulai saya baca.
Novel the Godfather misalnya, saya tandaskan hanya dalam jangka waktu tiga hari. Itu saya lakukan, setelah mengetahui bahwa film itu hasil adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Karena pada dasarnya saya penasaran, saya seperti digiring untuk lekas menamatkannya, tanpa kehilangan detail dan kenikmatan membaca. Dan ketika saya menandaskannya, ternyata keduanya sama-sama bagus. Saya juga membaca novel The Godfather berulang kali, sama seperti ketika saya tak jengah-jengah menonton filmnya.
Buku The Godfather bagus karena ia memberi detail cerita yang kaya akan data dan teknik penyajian. Setumpuk rahasia mafia Italia, lengkap dengan karakter-karakter yang dicangkok dari tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata, seperti hidup dan beraksi lagi di semesta lain yang diciptakan oleh si pengarang, Mario Puzzo. Detail-detail itu menjadi salah satu kekuatan dalam buku itu.
Karena memuat banyak detail dan data, Mario Puzzo mengkomposisikannya dalam ketebalan 600-an halaman. Tapi kekayaan cerita dan ketebalannya tak membuat jalan cerita terseok-seok. Terkadang ada jalan memutar yang harus dilakukan si penulis untuk menceritakan hal sampingan. Namun hal sampingan itu juga penting karena ia memberi petunjuk untuk memahami novel itu secara utuh. Kalau Puzzo tidak punya ketangkasan bercerita, bisa jadi pengolahan materi novel itu hanya menghasilkan cerita yang membosankan.
Sebagaimana novel The Godfather, buku Il Postino karya penulis Chile Antonio Skarmeta adalah novel yang mampu menyalin kehidupan orang lain dengan bagus, tepatnya cerita seorang tukang pos dan penyair legendaris Chile, Pablo Neruda. Novel itu, menceritakan bagaimana antara tukang pos dan Pablo Neruda terjalin sebuah hubungan hangat berkat keingintahuan soal puisi, perempuan, dan kebermaknaan hidup.
Hasilnya mengagumkan. Dengan 146 halaman saja -versi terjemahan-, semua yang ada dalam novel itu berjalan intens, seakan perjalanan hidup si Mario, sang tukang pos, teringkas lengkap dilengkapi gambaran akhir-akhir masa produktif pengarang besar, Pablo Neruda. Padu-padan cerita kedua tokoh itu, dibuhul lewat penggunaan bahasa yang canggih, tapi tidak terkesan pamer kemampuan. Kesederhanaan dan keindahan, menjadi dasar penulisan buku itu.
Fakta lain yang terungkap, Antonio Skarmeta menulis buku itu selama 15 tahun. Sepanjang masa penulisan novel pertamanya, penulis Amerika Latin lain seperti Mario Vargas Llosa sudah merilis novel kelima. Ia sendiri malu mengakui kemalasannya, tetapi untuk memulai penulisan novel pertamanya, ia harus melewati beberapa proses berliku, terutama ihwal menyeleksi data secara ketat. Terlebih ia harus meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai jurnalis.
Berbeda dengan dua penulis di atas, Knut Hamsun, seorang peraih Nobel Sastra dari Norwegia, menuntaskan penulisan novel monumentalnya, Lapar, hanya dalam jangka waktu dua minggu saja. Novel itu menceritakan seorang penulis yang menahan lapar selama berhari-hari lantaran tak punya cukup uang untuk membeli makan. Uang yang ia terima hasil dari menulis, hanya cukup untuk melunasi utang-utangnya.
Demi menyambung hidup, penulis dalam novel itu bertekad menciptakan suatu karya terbaik yang pernah ia buat sepanjang hidupnya. Itu disertai harapan, bahwa ada pemasukan cukup untuknya dan ia bisa melepaskan diri dari jerat utang beserta bayang-bayang para penagihnya.
Lapar karya Hamsun juga seperti membawa pembaca ke dalam kesadaran tokohnya. Membaca novel itu, pembaca akan mengerti bagaimana pergulatan pikiran yang dialami oleh si tokoh, lengkap dengan segala kemuraman, kesedihan, dan kemelut hidup yang memprihatinkan. Namun Lapar tidak lantas semata-mata menjadi kompleks dan alot dibaca, sebab Hamsun tahu persis bagaimana meramu materi mendasar jadi sebuah karya besar. Itu memudahkan pembaca mengikuti alur cerita hingga selesai. Sehingga, tak butuh waktu lama untuk menuntaskan novel Lapar.
Berbeda dengan Skarmeta atau Puzzo yang membutuhkan bertahun-tahun waktu penulisan karena menyeleksi ketat logika cerita dengan riset dan data, Knut Hamsun bisa menulis cepat karena ia merangkai ulang pengalaman singkatnya. Ketika mengetik, ia membiarkan apa yang ada dalam dirinya mengalir begitu saja. Dalam keadaan mengerang menahan lapar, semua cerita yang ada dalam dirinya, mengalir tak terbendung.
Barangkali apa yang dialami oleh Hamsun, adalah momen di mana proses kreatif seorang penulis, tengah mencapai klimaks kesadaran. Di titik itu, seorang penulis seperti mendapat ilham. Mereka yang mendapat itu akan menulis lancar tanpa hambatan, seolah-olah ada dorongan dari syaraf-syarafnya untuk terus bergerak mengetik cerita. Momen seperti ini tak selalu muncul, hanya mencuat sewaktu-waktu, dan kemungkinan hal itu bisa terjadi ketika penulis tengah bersikeras menjebol bendungan kesadaran dalam dirinya.
Alih-alih menulis novel dalam waktu singkat, terkadang mematangkan premis cerita saja bisa memakan waktu lebih lama. Untuk mematangkan premis cerita, ketenangan dan pengalaman seorang penulis sangat menentukan. Keberangkatan penulisan novel, dimulai dari sebuah kumpulan ingatan dan penalaran yang telah lama diasah. Di dalam kepala seorang penulis, lazim bersarang suatu kumpulan ingatan seperti benang kusut, dan penalaran mengurainya satu per satu menjadi sebuah premis.
Kerumitan menulis novel, lazim terjadi karena para penulis ingin mencari bentuk terbaik bagi karyanya. Mereka ingin para pembaca bisa memahami tulisannya, mengerti pesan yang ingin disampaikan, dan menikmatinya sebagai pengalaman psikologis yang berbeda. Beberapa berhasil meraih hati pembaca sekaligus mencapai bentuk terbaik, tapi sebagian ada yang baru sanggup mencapai separuh perjalanan. Itu semua karena proses. Ada serangkaian fase yang harus mereka tempuh. Tak semuanya mudah, kendati ada yang berhasil meraih hati dari rilisan pertama karena mereka bersua dengan keberuntungan.
Beberapa waktu lalu sempat beredar pamflet seminar penulisan novel dalam satu hari. Kalau berkaca pada penulis-penulis yang menghabiskan bertahun-tahun untuk melakukan pelbagai proses penulisan novel, saya cukup terkejut mendengar kabar itu. Sejauh yang saya tahu, mereka yang mengorbankan banyak waktunya untuk menulis novel, hasilnya seringkali bagus. Kadang bisa menyenangkan sekaligus menggetarkan. Tapi mereka yang bisa menulis dalam waktu singkat, atau beberapa hari juga tak kalah bagus. Mereka punya teknik untuk melakukan itu.
Namun saya belum pernah mendapat cerita ada seorang penulis novel yang sanggup menyelesaikan novelnya dalam satu hari saja. Dengan catatan, satu hari itu adalah proses eksekusi terakhir setelah rangkaian agenda penulisan yang lain tuntas. Proses kreatif seperti itu terdengar sangat sensasional. Tapi saya belum melihat karya para pengisi acara itu sebombastis embel-embel proses kreatif mereka.
Kata beberapa jurnalis yang kemudian banting setir menjadi penulis fiksi, menulis fiksi itu lebih sukar daripada menulis berbahan dasar fakta. Bila fakta tersedia, penulis dapat menyusun kepingan-kepingan yang ada dan semuanya bisa lekas selesai dengan tahap terakhir berupa verifikasi. Tapi fiksi berbeda, menulis karya fiksi membutuhkan penghayatan perasaan dan penggunaan pelbagai penalaran. Sementara di dalam karya fiksi, ada hal-hal krusial di luar penulisan berita pada umumnya seperti: penyelarasan imajinasi dan fakta, pembentukan karakter yang harus dikembangkan dari yang sudah ada, dan membangun konflik yang mengukuhkan cerita.
Pelbagai kerumitan itu, membuat saya menyesal tidak mengikuti seminar penulisan novel satu hari. Kalau saja saya sempat mendengarnya jauh-jauh hari, saya akan langsung ikut mendaftar. Itu disertai harapan, bahwa setelah mengikuti acara itu, saya bisa mendapat resep terbaik bagi penulisan novel, dan segera menjadikan acara seminar itu sebagai premis cerita untuk novel pertama saya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews