Perjalanan Jakarta-Nanchang pada 2020 ini ternyata harus ditempuh selama 16 hari. Dua hari di perjalanan. 14 hari di karantina. Dengan biaya total Rp 50 juta --dari biasanya hanya Rp 12 juta.
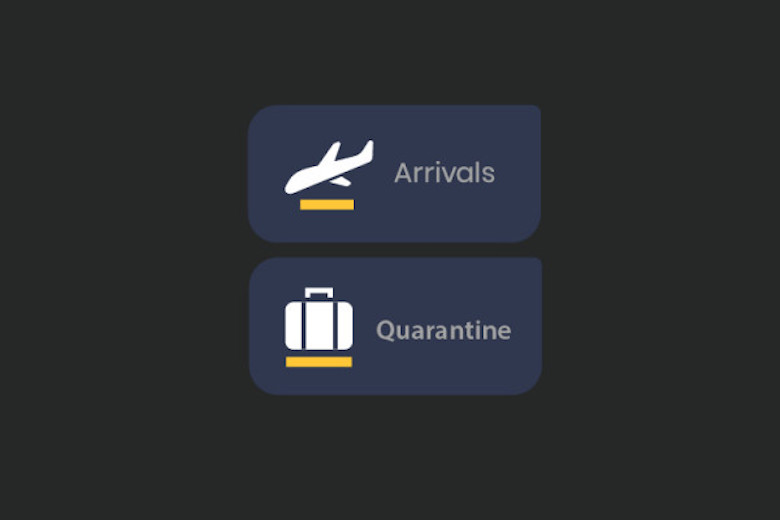
Saya punya teman yang bekerja di Indonesia. Sebagai tenaga ahli. Kontraknya hanya sampai 30 April 2020.
Sebelum berangkat ke Indonesia ia sudah punya tiket pulang: 30 April 2020. Dengan pesawat Garuda Indonesia.
Rumahnya di Jiangxi, tetangga Hubei yang beribu kota di Wuhan.
Sebelum Wuhan kena virus ia sudah di Indonesia. Saya menemaninya waktu ia harus berhari raya Imlek di negeri orang. Ia tidak bisa mudik karena tugas.
Ia begitu bangga tidak ada Covid-19 di Indonesia. Ia merasa beruntung berada di negara yang aman-virus. Ia selalu menelepon keluarga: betapa aman di Indonesia.
Tapi ia juga sangat mengkhawatirkan keluarganya di sana. Yang lagi bertahan terhadap gempuran Covid-19.
Lalu gantian.
Ketika akhirnya Covid-19 masuk Indonesia ganti keluarganya yang mengkhawatirkannya. Apalagi mereka dengar kian hari Indonesia kian berat. Sedang di kampungnya sendiri Covid-19 sudah teratasi.
Teman saya itu pun mempercepat kerjanya. Agar bisa selesai sebelum 30 April. Agar bisa cepat pulang.
Berhasil.
Tanggal 10 April tugasnya selesai.
Tapi ia tidak bisa pulang. Tidak ada lagi penerbangan dari Indonesia ke Tiongkok. Tiket pulang tanggal 30 April pun tidak bisa lagi diharap.
Tapi ia tidak sendirian.
Banyak juga orang lain yang seperti itu.
Ternyata selalu ada jalan keluar. Selalu.
'Pasar' jalur Indonesia-Tiongkok tetap ada. Meski tidak banyak lagi.
Peluang itu, sekecil apa pun, dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan penerbangan Tiongkok.
Airlines itu minta izin mengadakan penerbangan carter seminggu sekali. Memang tidak bisa lagi langsung dari Jakarta ke salah satu kota di Tiongkok. Izin untuk itu sudah ditutup --sejak Covid-19 merajalela di dua negara.
Tapi Indonesia masih mengizinkan penerbangan dari Jakarta ke Phnom Pehn, ibu kota Kamboja. Dan sebaliknya.
Indonesia adalah sahabat baik Kamboja. Kamboja adalah sahabat terbaik Tiongkok.
Dalam keadaan normal tidak ada penerbangan jurusan Indonesia-Kamboja. Pasarnya terlalu kurus.
Kebetulan Kamboja masih belum area merah. Jumlah penderita Covid-19 di Kamboja kurang dari 125 orang. Itu pun terbanyak dari keluarga Muslim di wilayah selatan. Yang tertular saat menghadiri acara besar Jamaah Tabligh di dekat Kuala Lumpur dulu itu.
Dari hari ke hari pertambahan penderitanya pun sangat kecil. Sudah beberapa hari ini tidak ada pertambahan. Bahkan tidak satu pun ada yang meninggal.
Kamboja telah dipilih oleh Tiongkok sebagai 'terminal transit' penerbangan carter. Khusus untuk penumpang kepepet dari Indonesia dan Filipina.
Dari Kamboja itu pesawat tidak boleh ke tujuan semauanya. Tiongkok sudah menetapkan dari Kamboja hanya boleh ke satu kota: Zhengzhou. Agar penanganan virusnya terkontrol.
Tiongkok sudah mengatur: pesawat dari negara mana harus mendarat di kota mana.
Justru Tiongkok sekarang yang khawatir Covid-19 kembali mewabah di sana. Yang sumbernya dari luar negeri.
Tapi Tiongkok juga tidak mau menutup diri. Harus tetap ada penerbangan ke Tiongkok --meski terbatas. Agar ekonomi tidak macet.
Kuncinya di kemampuan manajemen.
Seperti teman saya itu. Dari Kamboja ia harus terbang ke kota Zhengzhou dulu. Sejauh 6 jam. Padahal kampungnya tidak sejauh itu. Hanya persis di pertengahannya.
Di kota Zhengzhou ia harus masuk karantina. Penumpang satu pesawat dari Kamboja itu dimasukkan ke sebuah hotel. Hanya boleh di satu hotel itu. Agar pengawasannya terkontrol.
Begitu mendarat mereka diproses secara khusus. Harus mengisi banyak formulir. Mereka harus di hotel itu 14 hari. Setelah itu --kalau baik-baik saja-- barulah boleh pulang ke kampung masing-masing.
Di hotel itu mereka hanya boleh di kamar. Harus hanya di kamar. "Ke lobi hotel pun tidak boleh," tulis teman saya itu lewat WeChat-nya tadi malam.
"Siapa yang bayar hotel," tanya saya lewat WeChat pula.
"Bayar sendiri. Sesuai tarif hotel. Tarif normal," tulisnya.
Tadi malam itu sudah malam ketiga ia di hotel karantina itu. Masih 11 hari lagi baru boleh ke kampung.
Dari Zhengzhou nanti ia akan pulang naik kereta cepat. Yang harus melewati Wuhan.
Selama di hotel setiap hari ia harus lapor: berapa suhu badannya. Dua hari sekali. Di kamarnya memang disediakan alat pengukur suhu badan.
"Lapornya ke manajemen hotel. Lewat WeChat," katanya.
"Laporan saya selalu sama. Suhu badan saya 36.5 derajat Celsius," katanya.
Tapi ia tetap tidak bisa ke mana-mana. Biar pun Shaolin Temple di dekat situ. Biar pun kotanya Judge Bao tidak jauh dari situ. Saya, dulu, termasuk sering ke Zhengzhou --hafal makanan enaknya di mana saja.
Maka terjadilah apa yang harus terjadi. Perjalanan Jakarta-Nanchang pada 2020 ini ternyata harus ditempuh selama 16 hari. Dua hari di perjalanan. 14 hari di karantina. Dengan biaya total Rp 50 juta --dari biasanya hanya Rp 12 juta.
Tiongkok kini memang mengawasi ketat siapa pun yang datang dari luar negeri. Pun bila itu warganya sendiri.
Hampir semua penderita baru Covid-19 di Tiongkok belakangan ini adalah orang yang datang dari luar negeri.
Pendatang yang ODP-pun mereka terima. Dengan pengawasan lebih khusus. Dengan tempat karantina yang berbeda. Dengan perlakuan yang khusus: kaki mereka diberi gelang elektronik. Seperti yang dipakai --siapa itu-- di Vancouver, Kanada itu.
Dengan gelang kaki itu mereka ketahuan: meninggalkan tempat karantina atau tidak.
Ilmu manajemen --plus teknologi, plus leadership-- kelihatannya bisa diandalkan untuk mengatasi apa pun.
Kalau dilaksanakan.
Dahlan Iskan
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews