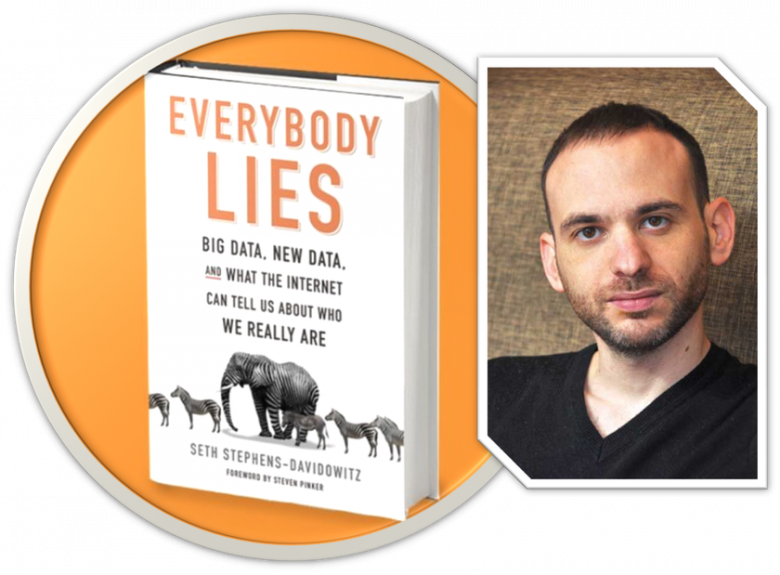
Ini buku serius yang saya baca bolak balik belakangan ini. Baca, ulangi, baca lagi, dan saya tetap terkesan. Everybody Lies karya Seth Stephens-Davidowitz. Buku ini menceritakan bahwa kita semua berbohong. Perbedaannya, hanya seberapa banyak kita berbohong. Ada yang sedikit dan ada yang banyak.
Tentang semua berbohong itu terus terang saya tidak kaget. Saya toh bukan orang yang memandang sesuatu hitam putih. Hanya fakta-fakta tentang berbohong yang dikemukakan Davidowitz itu yang membuat saya tercerahkan.
Pertama, makin tidak personal kondisi yang dihadapi seseorang, maka seseorang semakin jujur dalam memberikan informasi. Misalnya saat kita memberi info suatu alamat pada orang lain.
Tetapi begitu berhadapan dengan norma, etika, tata nilai yang membuat orang lain dapat memberikan penilaian pada kita, kita akan mudah sekali untuk berbohong. Davidowitz mencontohkan tentang kemenangan Trump pada Pilpres di Amerika. Semua orang mengira, sejak Obama berhasil menjadi presiden, rasisme bukan masalah sosial lagi di AS.
Ternyata tidak. Hanya beberapa menit setelah Obama menjadi presiden, Google dipenuhi pertanyaan-pertanyaan rasis dengan kata kunci kata-kata abusive seperti 'nigger'...
Sejak itu jumlah orang yang mengakses info-info rasis terus meningkat. Hingga puncaknya adalah kemenangan Trump. Meski semua survey nyaris tak ada yang meramalkan kemenangan Trump.
Davidowitz kemudian menuliskan hal yang sangat mencengangkan sekaligus mencerahkan saya. 'Orang tidak berkata jujur pada survey, karena mengakui berpihak pada Trump akan menunjukkan kecenderungan rasisme seseorang. Dan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, all men are created equal. Tak ada seorang pun yang ingin dianggap tak bermoral karena rasis, meski dalam hati ia mendukung rasisme.
Davidowitz kemudian menceritakan, hanya pada Google dan search engine lah manusia mau jujur. Bukan hanya mengakui semangat rasisnya, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang tak sanggup diungkapkan pada orang lain karena tak ingin dianggap tidak normal. Pertanyaan seperti kecenderungan seksual, keinginan bunuh diri atau balas dendam.
Singkatnya, data tentang akses ke suatu informasi di internet bisa menjadi alat analisis yang jauh lebih akurat, mengingat manusia cenderung jujur di depan mesin yang memang tak pernah menghakimi....
Dari situ saya berpikir tentang kecenderungan yang sering terlihat akhir-akhir ini. Eksklusivisme, menganggap diri dan kelompoknya terbenar. Yang lain salah, tak berhak berpendapat, kalau perlu dibasmi. Yang lain harus memahami.
Semua kecenderungan itu dipertontonkan secara vulgar. Hingga saya sering berpikir, yang terlihat saja sebuas itu, lalu bagaimana isi hati dan pikirannya? Tidakkah jauh lebih kejam lagi?..... Dan saya pun jadi penuh prejudice...
Atau jangan-jangan nilai-nilai yang dianggap benar dan berlaku umum memang seperti itu. Lalu salahkah saya, ataupun orang-orang lain seperti saya yang tak tahan melihat agresivitas dan kebuasan-kebuasan itu?
Saya teringat obrolan-obrolan dengan teman. Suatu kali kami membahas tentang pencerahan spiritual. Pencerahan spiritual yang paling umum dibahas, dan diceritakan ke orang lain adalah pencerahan saat saat seseorang mendapat panggilan relijius.
Saat orang yang selama ini hedonis, pemuja materi, lupa Tuhan tiba-tiba sadar dan mendapati hatinya kosong, kecuali bila ia mengisinya dengan ritual ibadah. Ada banyak kisah seperti ini, dan semuanya mengesankan.
Tetapi kemudian adalagi pencerahan tahap berikutnya yang jarang sekali diakui orang lain, karena tak ingin dianggap 'tidak waras' oleh orang lain. Pada fase ini seseorang biasanya telah cukup relijius. Menjalankan ibadat dan ritual dengan tekun. Tetapi kemudian mendadak terbentur kenyataan, mengapa banyak orang beribadat, tetapi kejahatan tak kunjung hilang. Bahkan kian hari kian banyak kejahatan dan orang teraniaya.
Di titik ini seseorang akan mempertanyakan keyakinannya. Apa guna keyakinan teguh bila dalam kesehariannya seseorang tak menjadi humanis, tidak menjadi lebih bermoral...
Saat di titik ini, saya melakukan apa yang ditulis Davidowitz, bertanya pada search engine. Karena pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya kemukakan tak sanggup saya katakan ke orang lain. Saya tak ingin dianggap tidak waras atau lebih jauh lagi dianggap orang jahat karena mempertanyakan hal-hal suci dan relijius.
Fase bertanya pada search engine itu mempertemukan saya pada banyak teman dengan pergumulan yang sama. Dan saya akhurnya bisa bebas dari rasa bersalah, menjalin persahabatan baru dengan mereka dan saling menguatkan.
Dengan berjalannya waktu, saya dan teman-teman terus bertumbuh pada pemahaman-pemahaman baru. Banyak yang menjadi non believer humanis. Ada juga yang mengakui adanya kekuatan yang mengatur semesta, meski bentuknya bukan sesuatu yang personal.
Ada pula yang seperti saya, menemukan ketenangan baru dalam ibadat-ibadat dan ritual-ritual. Tak lagi mempertanyakan kesesuaian suatu keyakinan dengan sains. Seorang teman saya menjadi rajin beritual terima kasih pada alam. Ada yang rajin bermeditasi. Sedang saya menemukan kesukacitaan dan keharuan saat mendengar lagu rohani dan doa-doa yang dipanjatkan dalam keteduhan.
Tetapi satu hal, ada benang merah yang sama di antara kami, kami telah melewati pergumulan untuk dianggap orang berdosa atau jahat. Ketenangan batin ternyata bukan melulu bergantung apa anggapan orang tentang kita. Kesejatian jauh lebih membawa kedamaian.
Bila dilihat dalam perjalanan spiritual saya saat ini, keberanian untuk mengikuti panggilan nurani itu mukjizat terbesar yang saya alami.
Amazing grace.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews