Saat para pegawai itu mulai memegang kapak dan kembali mendekati tubuhku, kuperiksa tempat bupati itu berdiri.
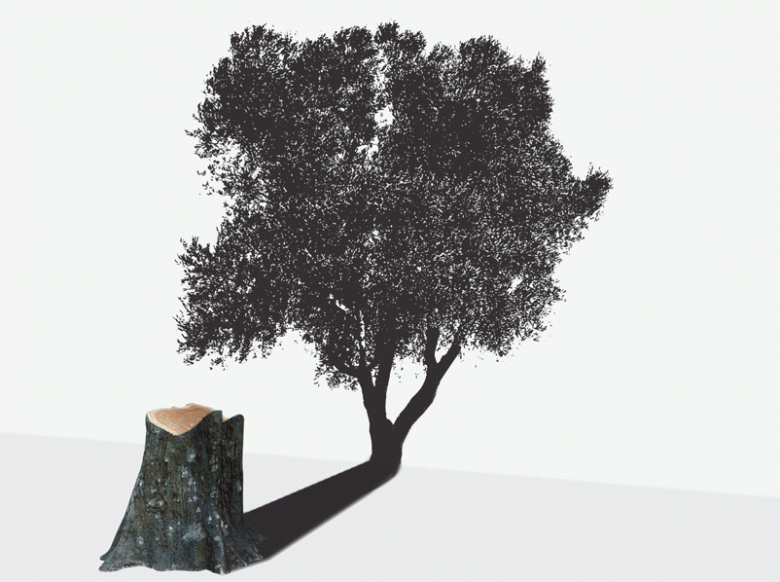
Kapak pemotong kayu itu kembali diayunkan dari tangan seorang pegawai honorer, tetapi sudah kukeraskan seluruh pembuluh dan kambiumku. Rasa perih tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhku ketika ujung kapak yang tajam itu diayunkan dan tertanamkan di kulitku. Namun, seperti kemarin-kemarin, hanya kulit saja yang sedikit terkelupas.
Setelah 10 menit mencoba, pegawai itu mundur sambil menggeleng kepala kepada teman-temannya. Seluruh ujung kapak yang tajam sudah kubikin tumpul ketika menyentuh lapisan terluar kulitku.
Sudah seminggu ini para pegawai menebangi pohon-pohon di sekitar kantor bupati lama ini. Hanya aku yang tersisa. Pohon beringin, angsana, dan lengkeng tak tampak lagi. Semuanya sudah ditebang dan akar-akarnya dicabut tanpa sisa. Pohon-pohon itu tak melawan ketika kapak yang tajam itu menyayat batang mereka. Kata mereka kepadaku, bupati ingin menata kantor bupati ini dan menggantingkannya dengan pohon-pohon cemara.
Namun, aku belum bisa mengikhlaskan diri menjadi tumbal. Aku lebih dulu lahir ketimbang siapa pun di kota ini. Kulitku menunjukan bahwa aku lebih tua dari usia manusia paling tua kota ini. Kusaksikan langsung jalannya sejarah! Begitu banyak yang kusaksikan hingga aku berani mengaku lebih bijaksana dari siapa pun, bahkan para bupati yang pernah menjabat dikabupaten ini.
Jika aku bisa menulis, mungkin sudah kutulis buku-buku tebal berisi hikmah dan pengetahuan untuk para warga dikota ini.
Ketika tubuhku belum setinggi pohon jagung, kota ini masih belantara lebat. Masih sangat sepi. Bahkan hukum yang berlaku disini hanyalah hukum hukum adat. Siapa berdarah bangsawan, maka dialah penentu kebenaran.
Selain hukum adat, hukum yang berlaku disini hanyalah hukum rimba. Siapa yang terkuat, dialah pemenang. Seekor biawak pernah memanjati batangku untuk menerkam musang yang bersembunyi di dahan paling tinggi. Tekukur, pipit, koak, dan sebagainya membangun kota dalam kerimbunan daun-daunku. Rumput lebih segar dan hijau di bawah naungan ranting serta dahanku yang membentang luas dan memberi teduhan bagi siapa pun tanpa membeda-bedakan ketika hari begitu terik.
Ketika tinggiku mencapai 7 meter, kusaksikan manusia pertama yang membawa katapel dan berburu burung tekukur disini. Juga masih kuingat laki-laki pertama yang membersihkan rumput dan bebatuan untuk membangun kantor pengadilan. Laki-laki itu sering bernaung di bawah tajukku untuk beristirahat. Sering pula ia tertidur hingga sore dan harus kubangunkan dengan tetesan air dari ujung daunku agar ia tak terlambat pulang. Selalu ia mengucapkan terima kasih kepadaku sambil tersenyum saat terjaga.
Aku tak tega jika laki-laki yang santun dan rajin itu pulang kemalaman. Aku dan dia sama-sama tak menyukai gelap, tetapi mungkin dengan alasan yang berbeda. Aku tak suka gelap karena, tanpa panas dan cahaya, aku tak bisa mengolah bahan makanan yang seharian kukumpulkan.
Setiap kali tubuhku bertambah, pengetahuan dan kebijaksanaanku juga bertambah. Lalu kutemukan cara paling manjur untuk mengelola makanan. Hasilnya, akar-akarku menjadi sangat kuat, sanggup menembus tanah yang sangat padat, dan bisa menjalar sampai jauh di bawah permukaan tanah. Jika perlu, bisa kusisihkan batu atau kerikil yang menghalangi pertumbuhan akarku. Karenanya, air bukan masalah bagiku. Akar-akarku sanggup mengisap air tanpa henti, dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu.
Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan seperti itu, siapa pun akan mafhum jika aku tumbuh menjadi raksasa: pada puncak usiaku sekarang ini, butuh satu orang dewasa untuk memeluk batangku. Namun, aku tak pernah takabur dengan kelebihan itu. Ketika kampung baru pertama dibangun di daerah ini, kuizinkan siapa pun memotong dahan dan rantingku untuk kayu bakar. Bahkan setelah kampung baru berubah menjadi kota yang ramai, tak pernah kutolak orang-orang yang berteduh di bawah ranting dan dahanku.
Tak kuingat lagi sudah berapa pasangan yang pernah bersandar di batangku dan bertukar ciuman sambil dipayungi daun-daunku. Aku menjadi saksi entah berapa ciuman pertama, gombalan-gombalan manis, dan pertengkaran-pertengkaran asmara disini. Aku menikmati cerita-cerita cinta itu karena aku pun merasakan keindahannya. Seringkali kutaburkan madu dan mengeluarkan bau harum di bagian dahan serta bungaku agar serangga tertarik dan membantu menyebarkan benih-benihku ke seluruh penjuru kabupaten ini agar bisa melestarikan keturunanku. Meski begitu, setaip hari keturunanku semakin berkurang. Padahal, akarku telah dijadikan sebagai lambang dari kabupaten ini. Bahkan dilambang dibaju dinas para pegawai negeri sipil itu.
Pernah kusaksikan kebodohan-kebodohan dari beberapa orang yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati. Mereka berpikir aku adalah penunggu tempat ini sehingga mereka perlu datang dan meminta restu. Mereka menaruh tempat sirih dan mulai berbicara seperti orang kesurupan. Mendengar pembicaraan mereka, membuat aku tersenyum geli. Aku hanyalah sebatang pohon cendana, bukan Uis Neno atau Uis Pah. Yang bisa kuberikan hanyalah teduhan dan bantuan untuk menghijaukan kantor bupati ini. Itu saja. Tidak lebih.
Kebodohan paling menyedihkan adalah keputusan seorang bupati yang berwatak feodal. Kepada salah seorang kepala dinas, ia mengungkapkan rencana untuk menebang pohon-pohon didepan bekas kantor bupati dan menggantikannya dengan pohon cemara. Katanya, menata dan membangun taman disini haruslah menggunakan pohon cemara. Tak baik kalau ada pohon cendana. Meski begitu, aku tahu maksudnya. Ia sebetulnya menginginkan batangku yang mulai berisi dan harum ini. Bupati ini, meskipun ia telah hidup di zaman modern, aku tahu pikirannya masih jauh tertinggal, masih seperti pemikiran orang zaman dahulu.
Itulah sebabnya aku tak terkejut ketika mendengar gagasan bodoh itu.
Gagasan bodoh memang akan selalu melahirkan tindakan bodoh.
Setelah para pegawai itu gagal menebangku untuk beberapa kali, tiba-tiba seorang kepala dinas mengundang seseorang yang terkenal dari dikaki gunung Mutis. Katanya, orang ini adalah penebang pohon terbaik. Ia sudah berulang kali menumbangkan pohon ampupu, kabesak, kayu putih dan lain-lain.
Saat penebang pohon itu mulai mengayunkan kapak, diam-diam kupatahkan dahanku yang agak besar, lalu kujatuhkan tepat menimpa kepalanya. Orang itu pingsan dan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit.
Setelah usaha terakhir yang mereka gunakan untuk menebangku pun sia-sia, mereka tak kehabisan akal. Tiba-tiba kulihat seorang kepala dinas berbicara di telepon. Sepertinya ia melaporkan kejadian itu kepada bupati. Dan benar, beberapa menit kemudian Bupati tiba dan memarkir mobilnya agak jauh dari tempatku berdiri. Laki-laki buncit berkacamata itu mendekat dan memarahi kepala dinas bersama para pegawai. Baginya, ini adalah kejadian paling konyol, dimana untuk menebang sebatang pohon cendana; bupati harus turun tangan. Beberapa saat kemudian, ia kembali memerintahkan agar sebelum menebang haruslah mengikat tali pada beberapa rantingku.
Saat para pegawai itu mulai memegang kapak dan kembali mendekati tubuhku, kuperiksa tempat bupati itu berdiri. Aku puas karena kakinya masih berada dalam jangkauan bayang-bayang dahanku. Ketika kapak mulai diayunkan dan menyayat batangku, kulemaskan pembuluh dan kambiumku. Bisa kurasakan saat aku terhuyung-huyung sementara beberapa orang menarik tali yang diikatkan di pangkal-pangkal dahan. Sebelum tumbang, kupastikan rantingku yang paling keras yang telah kusiapkan mengarah tepat di kepala Bupati. Bupati yang sombong itu akhirnya mati sebelum menghabiskan periode pertamanya.
***
Honing Alvianto Bana. Lahir dikota Soe, Nusa Tenggara Timur. Suka membaca dan menulis. Ia juga suka melamun. Saat ini ia sedang aktif bersama kawan-kawan pemuda GBKN.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews