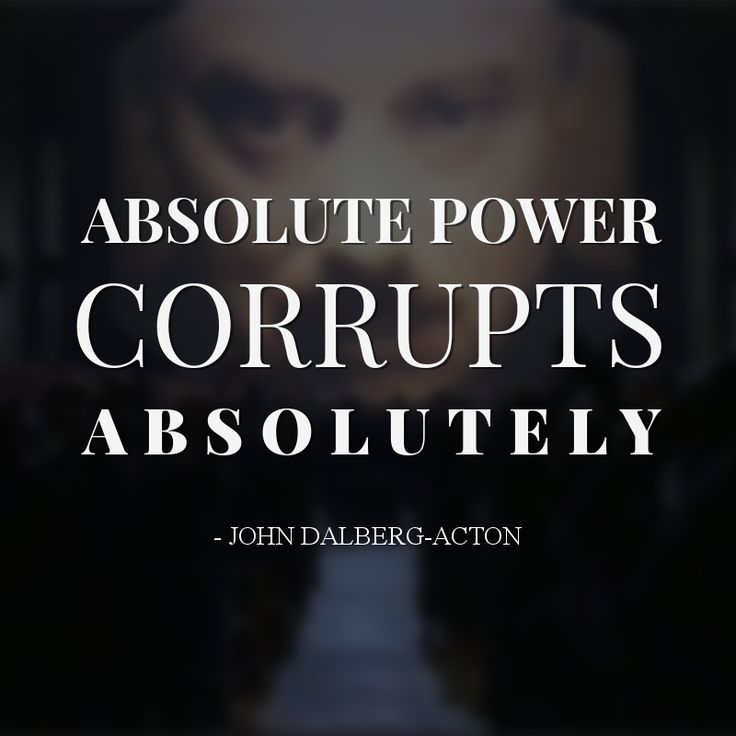
Cara termudah untuk meraih kekuasaan (power) pada masa sekarang adalah menjadi politikus. Bukan politikus sawah, tetapi politikus berdasi dan bermobil mewah. Tatkala “wahyu” kekuasaan sudah dihentikan dari langit, maka orang mencari cara lain untuk berkuasa. Mantan menteri, mantan tentara, dan petahana sama saja, berlomba meraih kekuasaan yang memang bikin ketagihan. Normalkah prilaku macam begini ini?
Tergantung dari niat, tergantung dari mana orang melihat. Dari sisi perintah Niccolo Machiavelli, kekuasaan harus diraih dan dipertahankan lewat cara apapun. Dari naluri primitif yang masih bersemayam pada hewan-hewan buas Afrika, kekuasaan diraih dengan cara menghabisi lawan.
Di zaman Soeharto, menjadi elite TNI adalah jaminan memegang tampuk kuasa di berbagai tingkatan, kecuali menyerobot Presiden RI itu sendiri. Sekarang pamor TNI, apalagi Polri, dalam bursa perebutan kekuasaan sudah sangat menurun. Jangan tersinggung kalau saya katakan kalah agresif dari politikus. Celakanya birokrat dan teknokrat kalau ingin melepas syahwat kuasanya, mereka harus menjadi politikus terlebih dahulu.
[irp]
Kalau sulit membuat partai politik, bisa menjadi anggota lalu kemudian menjadi pengurus partai. Berjenjang, tentu saja. Ada pengurus partai di pusat, provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan. Pengurus teras partai di pusat berkemungkinan menjadi anggota DPR RI yang berkantor di Senayan, pengurus partai di provinsi bisa membidik anggota DPRD Provinsi dan kursi gubernur. Anggota partai kabupaten/kota bisa duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota dan masih berkemungkinan mengincar kursi bupati/walikota.
Hanya saja kalau untuk mengisi kursi eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati/walikota, biasanya mereka harus sudah menjadi legislator terlebih dahulu. Bahkan untuk menjadi orang nomor satu negeri ini, Presiden RI, polanya yang bersangkutan sedang menjadi ketua umum partai politik.
Untuk itulah, politikus yang “ngebet” ingin menjadi calon presiden, mati-matian akan mempertahankan posisinya sebagai ketua umum partai politik. Sebisa mungkin saat proses Pemilu Presiden dilaksanakan, yang bersangkutan masih menjabat ketua umum partai.
Paling aman menjadi capres beretnis Jawa plus beragama Islam, seakan-akan jika kebetulan beretnis paling besar di Indonesia ini, setengah kemenangan sudah berada di genggamannya, apalagi ia seorang Muslim. Uniknya, para tim pemenangan masing-masing capres mendeklarasikan diri sebagai Jawa atau paling tidak berdarah Jawa. Ini realitas politik.
Dari pola seperti itu, kita sudah bisa menebak siapa saja para calon Presiden RI yang akan bertarung pada Pilpres mendatang. Tengok saja siapa para ketua umum partai yang sekarang sedang memegang kekuasaan di partainya masing-masing. Saya tidak usah menyebut nama-nama di sini.
Lalu bagaimana pola rekrutmen calon presiden. Biasanya yang menentukan tetaplah calon presiden dari ketua-ketua umum partai itu. Dia bisa mengambil dari militer atau polisi, bisa politisi, bisa birokrat, teknokrat, cendekiawan, agamawan, pengusaha atau tokoh masyarakat. Namanya juga untuk “ban serep”, calon wakil presiden biasanya kalah pamor dengan calon presiden.
[irp]
Burukkah seseorang memiliki syahwat berkuasa? Atau sebaliknya, burukkah seseorang jika sama sekali tidak memiliki hasrat berkuasa? Mengapa pertanyaan semacam ini sempat melintas di benak saya?
Itu karena dalam beberapa bulan ke depan panggung politik nasional kita bakal kembali dimeriahkan oleh hajat nasional, Pilkada serentak, sampai kelak Pemilu Legislator dan disusul Pilpres. Sudah pasti bakal tergelar arena perebutan kekuasaan dengan tensi tinggi di Ibu Pertiwi ini.
Yang satu ingin mempertahankan dan mengamankan posisinya sebagai orang nomor satu negeri ini, dan kalau konstitusi tidak memungkinkan karena sudah menjabat dua kali, setidaknya pengajuan calon presiden dipilih dari lingkungan keluarga dan kerabat dekat.
Yang lain ingin menaikkan statusnya dari posisi orang nomor dua menjadi orang nomor satu. Orang yang pernah mengenyam sebagai orang nomor satu atau orang nomor dua negeri ini ingin coba lagi merasakan empuknya kursi Istana. Orang-orang yang belum pernah menjadi orang nomor satu atau nomor dua negeri ini mencoba adu nasib merebut kuasa.
Jangan-jangan, hasrat dan syahwat berkuasa itu tidak beda jauh dengan hasrat purba dari prilaku manusia; bercinta. Bila hasrat telah usai, syahwat terpenuhi, lupalah arti sesungguhnya dari usaha jor-joran yang dilakukan sebelumnya. Lupalah esensi hasrat berkuasa yang sebenarnya amanah ingin menyejahterakan rakyat.
Jangan-jangan setelah syahwat terpenuhi, lupalah rakyat yang menjadi esensi dan nilai berkuasanya seseorang. Amanah tinggal amanah, rakyat tinggal rakyat, yang ada terus dan tanpa henti menikmati kekuasaan.
Apa sesungguhnya esensi dari kuasa itu? Mengapa ia begitu banyak dikejar sampai seseorang rela mengabaikan etika dan bahkan rela menjadi gila? Apakah pemimpin itu lahir secara kebetulan, sudah digariskan, atau bisa diupayakan lewat pengaruh dan uang? Bahkan ketika usai membaca The Will To Power Friedrich Nietzsche pun, konsep kuasa di mata saya masih tetap sebagai sebuah kabut misteri.
[irp]
Paling tidak melihat kenyataan yang terjadi di panggung sandiwara politik negeri ini, seorang pemimpin lahir karena kebetulan semata, bukan seseorang yang digariskan dari Atas sebagai pemimpin. Bukan pula seorang yang punya talenta dalam memimpin.
Menjadi pemimpin di negeri ini bukan karena upaya sistematis atau didasari ingin mengabdi kepada bangsa dan Ibu Pertiwi. Hasrat kuasa muncul karena untuk mengamankan asset atau membentuk “kerajaan” dengan keluarga dan kerabat dekat sebagai anggotanya. Jangan tersinggung kalau saya mengatakan pemimpin di negeri ini lahir karena punya pengaruh dan boleh jadi uang.
Pengaruh. Bisa karena ia berkuasa dan memegang kendali massa sebagai ketua umum partai atau ketua umum partai yang menunjuk jagoannya untuk berlaga. Uang. Ini tidak bisa didebat lagi. Nonsens mau jadi pemimpin di negeri ini tanpa keluar uang.
Gunakan pengaruh Anda agar para cukong dan centeng mendanai hasrat dan syahwat kuasa Anda. Sebagai imbalannya, nanti kasihlah cukong atau centeng itu sejumlah megaproyek. Masih ingat almarhum Nurcholish Madjid yang berniat ikut konvensi Partai Golkar pada 2004 lalu. Tanpa uang dan hanya bermodal panggilan nurani semata, terpentallah Cak Nur dan yang keluar sebagai pemenang konvensi adalah figur lain.
Anda ingin jadi ketua umum partai atau ketua organisasi massa? Jangan harap bisa jika tidak ada uang. Jangan-jangan untuk menjadi ketua OSIS saja sekarang calon butuh uang.
Percayalah, pemimpin seperti itulah yang akan kita dapatkan pada Pilkada dan Pilpres, siapapun yang keluar sebagai pemenangnya. Harap dicatat pula, pemimpin yang berhasil memimpin karena pengaruh dan uang harus mengembalikkan modal saat ia berupaya memenuhi syahwat berkuasanya secepat mungkin. Ia harus berterima kasih kepada cukong atau centeng yang membekinginya. Ini hukum ekonomi yang berlangsung terang benderang di ranah politik nasional.
Semoga di Pilkada serentak dan Pilpres mendatang "hukum ekonomi" itu sudah tidak ada lagi.
Bagaimana dengan nasib rakyat pemilik suara yang sudah menjatuhkan pilihan? Mungkin sudah saatnya mereka tidak lagi mengiba-iba minta diperhatikan, sebab para pemimpin itu mungkin takkan peduli di kursi kekuasannya yang masih hangat, nyaman dan empuk.
Rakyat cuma dibutuhkan saat hasrat kuasa telah memuncak mencapai ubun-ubun.
Crottt....!
***
[irp]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews